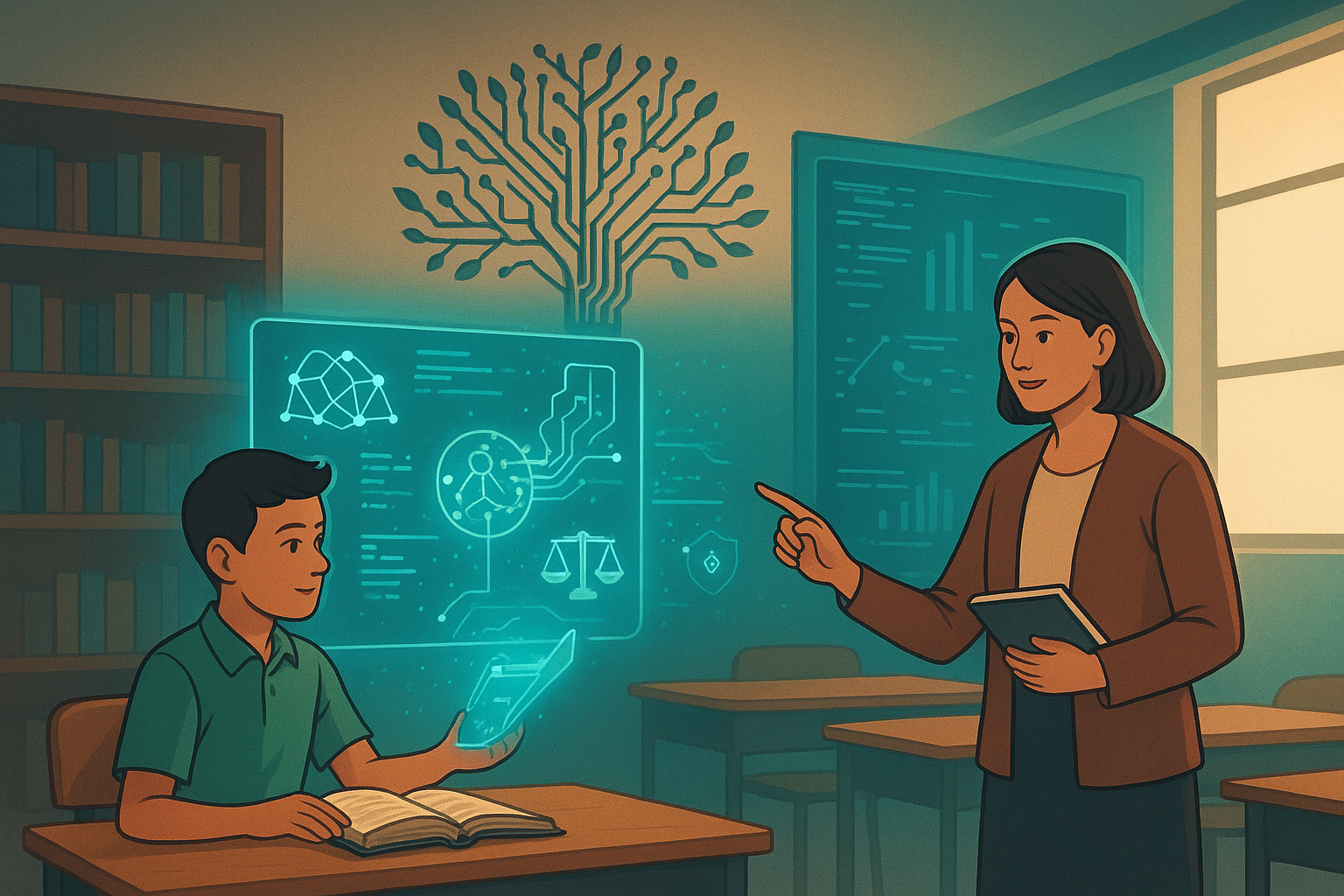
Sinyal dari Cambridge: Ketika Menghafal Menjadi Usang
Laporan The Crimson (Nov 2025) menyoroti desakan akademisi Harvard agar pemahaman AI menjadi kompetensi wajib lintas disiplin. Diskusi di sana bukan lagi “apakah siswa boleh menggunakan ChatGPT?”, melainkan “bagaimana siswa memimpin di dunia yang dikendalikan AI?”.
Sementara itu, sistem pendidikan Indonesia masih terjebak paradigma abad ke-19: guru sebagai satu-satunya sumber kebenaran, siswa sebagai wadah pasif. Padahal, data UNESCO 2024 menunjukkan lebih dari 60 universitas global sudah mengintegrasikan literasi AI dalam kurikulum inti.
Kontras ini mencolok. Harvard melatih “arsitek prompt” dan “auditor etika algoritma”, sementara banyak kelas di Indonesia masih menekankan hafalan. Tanpa perubahan drastis, generasi muda kita berisiko hanya menguasai keterampilan yang segera digantikan mesin.
Pedagogi Transformatif: Melatih Apa yang Tak Bisa Dikoding
Pedagogi transformatif di era AI menuntut kita untuk mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan kecerdasan manusia. Dalam pendidikan tradisional, kemampuan mengingat dianggap sebagai fondasi. Namun, di era algoritma generatif, mesin memiliki ingatan yang sempurna dan tak terbatas. Piramida pembelajaran yang selama ini menempatkan hafalan di dasar harus dibalik: fokus pendidikan harus segera melompat ke tingkat tertinggi, yakni mencipta, mengevaluasi, dan menganalisis.
Seperti yang ditegaskan Dr. Ratna Sari, Psikolog Pendidikan Universitas Indonesia, “Jika lulusan hanya unggul dalam kepatuhan dan hafalan, mereka akan kalah dari algoritma. Pendidikan harus melatih otot yang tak dimiliki AI: empati, moralitas, dan kreativitas radikal.” Pernyataan ini menyoroti bahwa keunggulan manusia bukan pada kemampuan mengulang informasi, melainkan pada kapasitas untuk memberi makna, menimbang etika, dan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada.
Namun, tantangan besar muncul ketika akses terhadap kurikulum AI hanya tersedia di sekolah internasional atau universitas elit. Jika hal ini dibiarkan, kita sedang membangun jurang sosial baru: mereka yang memerintah AI dan mereka yang diperintah oleh AI. Demokratisasi kurikulum menjadi keharusan, agar anak di pelosok desa pun memahami bahwa informasi di media sosial mereka dikurasi oleh mesin, dan mereka mampu memanfaatkannya untuk produktivitas lokal.
Di sisi lain, pendidikan AI tidak boleh berhenti pada aspek teknis seperti coding. Ia harus menjadi ruang filsafat dan kewarganegaraan, tempat siswa diajak berdiskusi tentang bias data, privasi, dan dampak sosial teknologi. Di sinilah konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara menemukan relevansi baru: membebaskan manusia dari penindasan algoritmik, menjadikan teknologi sebagai alat pembebasan, bukan pengekangan.
Membangun Manusia Utuh: AI sebagai Mitra, Bukan Tuan
Jika kita berhasil mengintegrasikan pedagogi transformatif ini, maka akan lahir generasi “Centaur”—manusia yang kemampuannya diperkuat oleh AI, namun tetap memegang kendali moral. Mereka akan menjadi pemimpin yang mampu menggabungkan ketajaman algoritma dengan kebijaksanaan manusia. Tetapi jika kita gagal, risiko yang menanti adalah ledakan pengangguran struktural di kalangan pekerja kerah putih, yang keahliannya menjadi redundan karena digantikan mesin.
Pertanyaan reflektif pun muncul. Bagi pendidik, apakah tugas yang diberikan kepada siswa masih relevan jika bisa diselesaikan oleh ChatGPT dalam hitungan detik? Jika tidak, maka tugas itu bukan lagi ukuran kecerdasan manusia. Bagi orang tua, apakah kita mendidik anak untuk sekadar meraih nilai ujian sempurna, atau untuk menumbuhkan rasa ingin tahu yang membuat mereka berani bertanya di luar kelas?
Implikasi kebijakan publik juga tak bisa diabaikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus segera melakukan moratorium terhadap metode pengujian berbasis hafalan, menggantinya dengan penilaian berbasis proyek. Model ini tidak hanya mengizinkan penggunaan AI, tetapi juga menuntut siswa untuk mengkritisi, memperbaiki, dan mempertanggungjawabkan output mesin. Dengan demikian, pendidikan tidak lagi sekadar melahirkan penghafal, melainkan manusia utuh yang mampu berdialog dengan teknologi tanpa kehilangan jati diri.
.
🛎️ Jeda Sebelum Share
Berhenti sejenak. Sebelum membagikan artikel ini, tanyakan: Apakah kita melihat AI sebagai ancaman yang harus dilarang di kelas, atau sebagai cermin untuk memperbaiki cara kita mengajar?
📚 Sumber Transparan
- The Crimson: “Wyche: Harvard AI Education” (18 Nov 2025)
- World Economic Forum: Future of Jobs Report (Education Edition)
- UNESCO Global Education Monitoring Report 2024
- Kajian Pedagogi Kritis Ki Hajar Dewantara (Merdeka Belajar di Era Digital)
- Kemdikbud RI: Strategi Transformasi Pendidikan Digital 2025
🔗 Bacaan Lanjutan
- Yuval Noah Harari, 21 Lessons for the 21st Century (Bab Pendidikan)
- Esai: Mengapa Guru Tidak Akan Tergantikan, Tapi Guru yang Tidak Memahami AI Akan Tergantikan
- Artikel: AI Literacy in Southeast Asia: Opportunities and Risks





1 thought on “Evolusi atau Eliminasi? Mengapa Kurikulum AI Bukan Sekadar Menambah Mata Pelajaran”